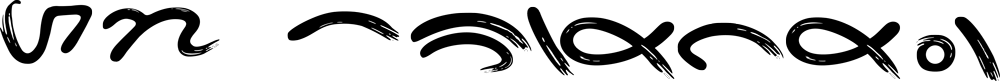Dalam kurun waktu tiga bulan, Ahu Parmalim telah diputar di hampir 100 layar komunitas. Perlahan tapi pasti melahirkan obrolan dan menyalakan api kewarasan untuk merayakan perbedaan.
Tiga bulan telah berlalu sejak Ahu Parmalim dirilis oleh Yayasan Kampung Halaman pada 16 November 2017 lalu. Pada hari rilisnya, lebih dari 40 titik di berbagai kota di seluruh Indonesia memutar film ini secara serempak sebagai salah satu cara merayakan Hari Toleransi Internasional yang jatuh di hari yang sama. Seperti langkah-langkah kecil yang dirajut jadi gerak lari yang hebat, film ini terus menemukan ruang untuk hadir ke publik yang lebih luas dan melahirkan banyak hal baru selama perjalanannya.
Menghadirkan sosok Carles Butar-Butar, seorang remaja penghayat asal Balige, Samosir, film ini membawa narasi soal agama kepercayaan dan toleransi. Sebagai remaja asli dari suku Batak, Carles dan keluarganya memilih untuk memeluk agama asli kepercayaan moyangnya, yaitu Ugamo Malim. Para penghayat Ugamo Malim menyembah Debata Mulajadi Nabolon sebagai penguasa semesta tertinggi. Ugamo Malim, seperti juga 244 agama kepercayaan lain yang terdaftar di Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, mengajak pengikutnya untuk menghidupi kembali budaya asli mereka yang dekat dan selaras dengan alam.
Film dokumenter garapan Cicilia Maharani ini memang minim konflik. Sepanjang 24 menit durasinya, kita akan melihat keseharian Carles sebagai remaja yang tak jauh beda dengan kita. Keminiman konflik di Ahu Parmalim bukan tanpa tujuan. Alih-alih menyoroti perbedaan seperti film-film serupa lainnya, Ahu Parmalim akan membuat kita bertanya seberapa banyak persamaan kita dengan mereka yang berbeda. Ia seperti pengingat untuk kita, bahwa ketika tiba pada soal perbedaan, kadang kita terlalu ribut dan membesar-besarkan sehingga lupa bahwa sebenarnya kita tak seberbeda itu. Dari kelindan konflik di lapangan yang rumit, Ahu Parmalim hadir bukan sebagai penyedia solusi atas isu diskriminasi dan intoleransi yang akhir-akhir ini memuncak kembali. Ia justru seperti pemantik kecil untuk melahirkan obrolan soal isu perbedaan, dalam kasus ini penghayat kepercayaan, untuk didiskusikan.

Selama tiga bulan, Kampung Halaman menerima hampir 100 rencana pemutaran dari berbagai komunitas di seluruh Indonesia. Dari data yang tercatat, hingga 23 Februari 2018 sudah ada 98 layar komunitas yang memutar Ahu Parmalim. Titik pemutaran ada di 48 kota yang tersebar di 17 provinsi, termasuk 2 titik putar di Duke University di North Carolina, USA dan The University of Melbourne. Para perancang pemutaran adalah beragam komunitas yang juga menggarap isu-isu yang berbeda. Cicilia Maharani menjelaskan bahwa tiap pemutaran bisa menjadi tempat berbagi pengetahuan tentang penghayat yang mungkin adalah hal baru bagi banyak dari kita. “Ada beragam sudut pandang muncul tentang penghayat, dilihat dari segi hukum, sastra, lintas budaya, sejarah, dll. Ada beragam penghayat lain yang angkat bicara tentang keberadaan merekayang selama ini ‘tak terlihat’,” ujarnya.
Banyak cerita menarik yang datang dari diskusi paska pemutaran. Seperti misalnya ketika Ahu Parmalim dibawa ke kampung halamannya sendiri di pemutaran yang diadakan oleh Tunas Naimbaru, komunitas pemuda parmalim di Medan, Sumatera Utara. Pemutaran diadakan pada 18 November 2018 di Kompleks Parmalim seusai ibadah Marari Sabtu. Tak hanya umat Parmalim yang hadir, tapi juga ada warga umum. Diskusi mengalir seru setelah film diputar karena penonton melihat keseharian mereka hadir dalam kemasan film di layar. Yang menarik, ada seorang penganut Islam Ahmadiyah yang berdomisili di Medan, hadir dan justru merasakan banyak kesamaan setelah menonton Ahu Parmalim. “Saya malah merasa memiliki banyak persamaan nilai dengan Parmalim, misalnya memakai sarung, hormat kepada pemerintah, dll. Sehingga tidak ada alasan bagi saya untuk mendiskriminasi atau tidak toleran. Saya merasa Parmalim adalah keluarga saya, saya akan sering datang kemari (Istana Parmalim).”
Jarak ternyata tak menjamin penyampaian informasi. Pemutaran yang diadakan oleh Aliansi Sumut Bersatu (ASB) pada 16 November justru menghadirkan diskusi yang sangat mendasar soal Parmalim. Meski bertempat di Medan yang tak jauh dari tanah asli lahirnya Ugamo Malim, beberapa mahasiswa yang hadir di pemutaran masih tak tahu apa itu Parmalim. Alhasil diskusi berkutat di isu awam soal penghayat, termasuk status hukum para penghayat kepercayaan di Indonesia. Hal seperti ini juga banyak terjadi di titik pemutaran lain. Sebagai perkenalan, film Ahu Parmalim membuka banyak keingintahuan soal agama kepercayaan.
Lain cerita dengan diskusi pada hari yang sama di pemutaran oleh Malabar Project di Malang. Menurut Muhammad Sabiq, meski isu toleransi ini sudah lama hadir, tapi Ahu Parmalim memberi refleksi kembali. Sebanyak 39 penonton yang hadir setelah itu berkutat pada diskusi soal penting tidaknya kolom agama di KTP kita. Sebagian penonton setuju kolom agama diadakan untuk mempermudah administrasi. Mereka yang tidak setuju menyatakan bahwa itu justru akan memunculkan gesekan konflik antar kelompok agama. Menariknya, pemutaran di Malang ini justru melibatkan Ikatan Mahasiswa Sulawesi Selatan. Alhasil, terjadi kolaborasi antar budaya di satu titik dari konten acara, penyelenggara, dan lokasi serta audiensnya.
Beralih ke Gorontalo, pemutaran di hari rilis Ahu Parmalim diadakan di Universitas Negeri Gorontalo dan dihadiri sebanyak 21 penonton. Selesai pemutaran, Defry Sofyan bercerita sempat muncul pembahasan soal Dayango, agama lokal di Gorontalo yang juga mendapat tekanan dari pemuka agama mayoritas dan pemerintah. Mereka sangat menyayangkan hal ini. Diskusi sempat beralih menyorot dua pemeluk agama Hindu yang hadir sebagai penonton. Jika agama kepercayaan mengalami diskriminasi, ternyata penganut agama legal minoritas pun tak jauh beda. Komang, salah satu penganut agama Hindu yang hadir ternyata mengakui juga bahwa ia pun masih merasakan adanya diskriminasi di kehidupan kesehariannya.
Respon lain datang dari Semarang. Pemutaran diadakan di Universitas Wahid Hasyim oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Penonton yang hadir sangat beragam, misalnya dari perkumpulan Rasa Dharma, Sekolah Teologi Agama Budha Syailendra, GUSDURian, kalangan seniman, wartawan, akademisi, relawan, karang taruna, dan sebagainya. Salah satu kesimpulan diskusi yang menarik adalah bahwa penonton yang mayoritas berasal dari suku Jawa tersebut mengaku cukup tertampar dengan kenyataan yang ada di film Ahu Parmalim. “Sebagai tanah yang terkenal keras, rupanya toleransi begitu di junjung. Lihatlah mereka bisa hidup berdampingan. Tamparan keras bagi masyarakat Jawa yang dikenal lembut namun kasus penolakan masih terjadi, seperti yang terjadi di Tegal dimana aliran kepercayaan Sapto Dharmo ditolak dalam pemakaman, lantaran bukan muslim”, ujar Nc Octavian.

Di Tulungagung, pemutaran Ahu Parmalim juga didatangi banyak penghayat, bahkan diskusi hari itu membahas tak hanya dari satu agama kepercayaan. Menurut catatan yang ditulis Diah Rizki dari Forum Komunikasi Seni Tulungagung, dibahas juga agama kepercayaan Sapto Dharmo, Sumarah, Kapribaden, Trimurti, dan lain-lain. Ditulis di blognya, “Mbak Monish dan Pak Ridho sama-sama setuju bahwa penghayat justru nguri-nguri ilmu terapan yang diajarkan orang tua zaman dulu. Bagaimana di rumah ada ruang sakral, juga ritual-ritual ngroso sebagai komunikasi dengan alam. Penghayat sangat dekat dengan alam karena pada satu titik mereka memahami bagaimana harmonisasi alam dan manusia.”
Masih dari pulau Jawa, ada juga cerita dari komunitas Sangkanparan di Cilacap. Penonton yang hadir justru didominasi penghayat kepercayaan Kejawen. Kisah Carles Butar-Butar di Ahu Parmalim memancing Mijil, seorang remaja penghayat Kejawen untuk turut membagi ceritanya yang ternyata tak jauh beda dengan yang dialami Carles. Penonton lain pun banyak bertanya kepadanya soal perlakuan guru agama di sekolah Mijil, atau tanggapan teman-teman seumurannya terhadap kepercayaannya yang berbeda. Ayah Mijil, Darman yang juga hadir juga turut bercerita bahwa nasibnya tak jauh beda dengan kaum minoritas lain di Indonesia. Ia bahkan sebenarnya membebaskan Mijil untuk memeluk agama apapun yang ia mau, termasuk agama resmi pemerintah supaya tidak mengalami diskriminasi sepertinya namun ternyata Mijil tetap memilih menganut Kejawen yang merupakan agama asli suku Jawa.
Munculnya diskusi-diskusi kecil di banyak tempat seperti ini adalah sinyal bagus. Pertanda bahwa ide soal toleransi dan perbedaan makin banyak dibicarakan dan dipahami oleh banyak orang. Di hari-hari dimana kasus intoleransi makin banyak ini, film Ahu Parmalim menemukan urgensinya untuk disiarkan ke publik luas. Menyoal perbedaan sejatinya adalah menyoal hidup kita sendiri. Makin kita terbuka dengan isu soal perbedaan dan toleransi, makin kita akan sadar bahwa justru penyeragaman adalah hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan. “Semoga film ini semakin luas ditontondan didiskusikan, menciptakan kesempatan bagi siapapun untuk belajar berdiskusi dengan hati dan pikiran yang terbuka, tetutama para remaja dan anak muda,” ujar sang sutradara.
Distribusi film Ahu Parmalim akan terus dilakukan dengan harapan makin banyak menemukan layar putar baru, mencapai penonton baru, dan yang terpenting memunculkan dialog dan wacana baru. Dialog-dialog yang lahir setelah film Ahu Parmalim ini diputar serupa benih-benih kecil yang membentuk jaringan ide, yang kelak di kemudian hari, akan sama-sama tumbuh besar dan saling terhubung. Menciptakan sebuah ekosistem yang menumbuhkan akal sehat untuk bersikap bijak terhadap perbedaan. Helen Keller pernah menulis, ‘the highest result of education is tolerance”, sebagai masyarakat terpelajar, harusnya secara otomatis kita akan meanggukkan kepala membaca kalimat tersebut.